Ziarah Bahasa Om Ben
- Ilham Nurul Karim
- Mar 13, 2017
- 4 min read

Busan keempat tinggal di Indonesia, Om Ben sadar telah bisa berbicara lancar tanpa ragu-ragu lagi menggunakan bahasa Indonesia. Karena saking bahagianya ia mau nangis, akunya. Ia bisa melakukan wawancara dalam bahasa yang dahulu asing baginya, bahasa Indonesia. Lelaki berkacamata ini sejujurnya tak mudah tersipu, tetapi lain kejadiannya ketika sebuah pujian diutarakan oleh nonya tua yang diwawancarainya. “Saya perhatikan Saudara tahu betul cara menggunakan padahal, jadi Saudara berpikir dalam bahasa Indonesia.”
Pandai melafalkan bahasa asing sebagaimana melafalkan bahasa ibu tidak sama rasanya dengan ketika mempelajarinya. Tahapan itu membenturkan dua perbedaan budaya dan logika bahasa. Hal demikian diperparah bila tingkat keragu-raguan dan rasa malu berada di stadium tinggi. Sementara mempelajari bahasa baru butuh sikap nekad dan berani salah. Kelas-kelas bahasa yang pernah terikuti ternyata tak seratus persen sama hasilnya bila pembelajar disamping belajar di kelas juga belajar langsung di lapangan. Om Ben mengalami fase belajar di kelas dan di lapangan.
“Sementara itu, saya mengambil kelas bahasa Indonesia di bawah supervisi John Echols dan dua mahasiswa Indonesia dan sangat menikmatinya. Betapa gembiranya saya belajar sebuah bahasa Asia, dengan aturan dan bebunyian yang tidak ada dalam “Eropa saya”! Saat itu saya belum tahu apa yang saya sadari kemudian—bahwa tiga tahun belajar bahasa di ruang kelas tidak ada artinya dibanding enam bulan berkutat dalam kehidupan sehari-hari di negeri asing.”
Apa yang Om Ben bilang adalah pengalaman pribadi yang tentu merupakan sesuatu yang subyektif. Hal ini tidak bisa disamaratakan dengan orang lain yang barangkali memiliki metode lain dalam menunjang keberhasilan pembelajaran bahasa, belum lagi dunia kontemporer telah banyak menyuguhkan pelbagai aplikasi belajar secara asyik. Namun, kita harus menyetujui kebenaran umum bahwa bahasa harus dipraktikkan secara intens. Om Ben menyimpulkan bahwa belajar di lapangan meski dengan durasi yang lebih sedikit lebih memberinya perubahan mencolok ketimbang belajar di kelas dengan durasi lebih lama. Siapakah Om Ben?
Om Ben ialah nama panggilan sederet sastrawan dan kaum intelektual Indonesia pada Benedict Anderson. Dialah peneliti yang memiliki spesifikasi pada kajian wilayah Asia Tenggara. Sayangnya, meski dengan segudang prestasi yang telah diraihnya, pria kelahiran Tiongkok ini pernah mengalami kesialan. Ya, dialah salah satu korban dari sebuah rezim otoriter yang pernah berjaya di Indonesia. Ia terusir dari Indonesia sebab Cornell Paper-nya yang ia kerjakan bersama karibnya terdakwa membahayakan bagi si pemegang tampuk kekuasaan waktu itu.
Masa kecil dilalui dengan prilaku yang menggelisahi pikirannya seperti ajakan membaca tentang kehidupan, tentang pengalaman, pemikiran orang-orang yang berbeda bahasa, berada di kelas dan wilayah yang berbeda, serta berasal dari periode kesejarahan yang berbeda. Hal demikian didukung pula dengan cara hidup tak ajeg meninggali sebuah wilayah. Sementara itu masa mujur Ben ialah ketika tanpa disadarinya tengah berancang-ancang menanggungjawabi kosmopolitan dan komparatif akan kehidupan. Di usia akil balig, ia menyebrang dari pelbagai negara : Yunnan, California, Colorado, Irlandia merdeka, dan Inggris.
Waktu itu, pria kelahiran 1936 ini tinggal di Irlandia, tetapi bahasa pertama yang dituturkan peraih Award for Distinguished Contributions to Asian Studies ini ialah bahasa Vietnam, bukan Inggris. Sejak lahir ia telah diasuh seorang wanita yang ia juluki ‘amah’. Kabarnya, wanita tersebut merupakan korban pelarian dari sebuah perjodohan paksa di negeri asalnya, Vietnam.
Benedict Anderson kecil mengesampingkan bahasa nasional negaranya, Irlandia. Hukum negara kala itu memutuskan bahwa siswa harus mempelajari bahasa nasional dan bahasa Latin. Nyokapnya bilang tak ada gunanya mempelajari bahasa yang hampir punah. Mungkin yang dimaksud adalah bahasa nasional, sebab kala itu masyarakat Irlandia sangat sedikit yang menguasai bahasa Irlandia. Maka dari itu, dipilihlah bahasa Latin sebagai bekal yang nantinya akan bermanfaat sekali dalam mempelajari bahasa Eropa yang lain. “Latin adalah ibu dari semua bahasa Eropa Barat (Prancis, Spanyol, Portugis, dan Italia),” kata nyokapnya. “Jadi kalau kau bisa Latin, kau nanti akan merasa semua bahasa tadi gampang. Lagipula, Latin punya kesusastraan hebat yang harus diketahui oleh setiap orang terpelajar,” alasannya.
Dengan meletakkan pentingnya pendidikan bahasa, maka bersama adiknya (Perry Anderson), Om Ben kecil disekolahkan di Inggris. Sekolah ini menggunakan kurikulum yang begitu mementingkan bahasa Latin (dan Yunani). Dua orang yang melekat dalam ingatan cucu seorang Anglo-Irlandia ini selama bersekolah di Eton adalah yang memperkenalkan padanya seorang penyair penerima Nobel, T.S Eliot. Dialah guru sastra Inggris. Selanjutnya adalah Sir, Robert Birley, kepala sekolah yang merambah sebagai guru sastra. Ia mengajar puisi. Berkat dua orang inilah apresiasinya terhadap sajak meningkat. Wah!
Di Eton pula, kegiatan menulis menjadi tradisi yang sangat diapresiasi. Ben kecil menggubah karya berupa sajak, mempelajari sajak, dan menerjemahkan karya sendiri dan penyair lain ke dalam bahasa Latin. Mendalami sajak dari begawan prosa Inggris abad ke-16 hingga 19 juga telah dilakukannya. Sastra sebagai obyek belajar bahasa. Wah! Lantas bagaimana apresiasinya terhadap seni pertunjukan?
Penulis buku Imagined Communities ini harus mendeklamasikan puisi dalam aneka bahasa tanpa sebuah teks (hafalan). Sewaktu masih sugeng, ia pamer bahwa dalam tempurung kepalanya masih tersimpan puisi berbahasa Latin, Yunani, Perancis, Jerman, Rusia, bahkan Jawa.
Pengembaraannya di pelbagai negara berjalan dengan tidak mudah. Ia seringkali memicu tawa dari teman-temannya lantaran aksen bahasa dan idiom-idom yang tak diketahui. Tetapi itu tak diartikan negatif olehnya. Ia justru merasa diuntungkan karena hal itu menciptakan tali hubung dengan negara-negara tersebut. Karenanya pula, dengan pengembaraan yang kian luas, di kemudian hari Om Ben merasa dipermudah dengan hubungan yang ia jalin hingga memiliki keterikatan mendalam (ikatan batin) pada negara Indonesia, Siam (Thailand), dan Filipina. Ada sebuah nasihat menarik dari Om Ben dalam otobiografinya, Hidup di Luar Tempurung. Ia mengumpamakan orang yang anteng dan ajeg dalam kediamannya, sama halnya dengan katak dalam tempurung. Katak yang duduk di tempurungnya akan merasakan ketenangan, lama-kelamaan ia sadar bahwa itulah semestanya. Ia jadi berpikiran sempit, picik, dan berpuas diri. Om Ben terkesan menyerahkan diri sebagai orang yang patut dicontoh dengan menziarahi pelbagai tempat.
‘Wah’ sekali bukan menyelami ziarah bahasa bersama Om Ben kecil? Om Ben kini telah beristirahat dengan tenang, tetapi semangat belajarnya akan tetap lestari, seperti karya-karyanya yang selalu dipuji dan diperbincangkan. Andaikan kita memiliki kesempatan pendidikan dengan apresiasi bahasa berikut sastra dan kebudayaan yang tinggi, andaikan politisasi besar-besaran pada produk kebudayaan kita tak terjadi, andaikan… andaikan saja. Maka, sebagai penutup, sebagai ungkapan kecemburuanku pada masa kecil Om Ben, aku meminjam kata Bandung Mawardi (esais dan kritikus sastra asal Solo) yang tertera dalam https://bandungmawardi.wordpress.com/ “Aku cemburu, tapi tak berirama.”
Rujukan Hidup di Luar Tempurung (Cet. 1, 2016) http://indoprogress.com/2016/07/pasca-brexit-inggris-goyah-keminggris-kokoh/ Bandungmawardi.wordpress.com
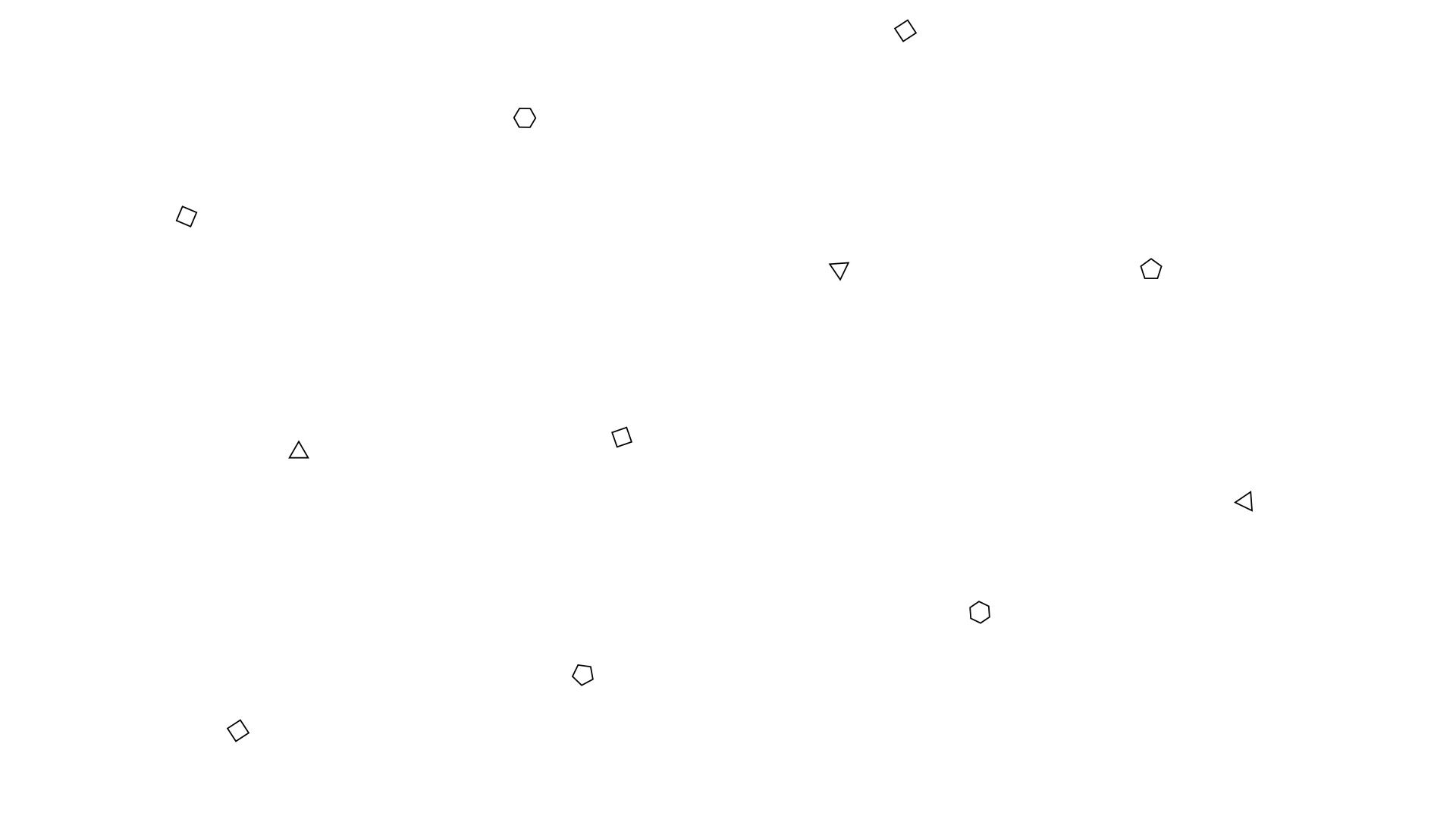
Comments